- Waspada!! Data Pribadi di Etalase Internet
- Wajah Pendidikan Indonesia
- Mengukir Kedaulatan Siber Menuju Indonesia Emas 2045
- Resolusi Jihad Santri Abad 21 Menuju Peradaban Dunia
- Pendidikan Penyelamat Lingkungan
- Awas!! Jaga kETIKAnmu
- Pendidikan Menajamkan Nalar Kritis
- Menjadi Generasi Cakap Digital
- Pondasi Literasi Digital
- Sudut Pandang Lain Penggunaan Chromebook
Paradoks Digital diruang Demokrasi
Paradoks Digital diruang Demokrasi
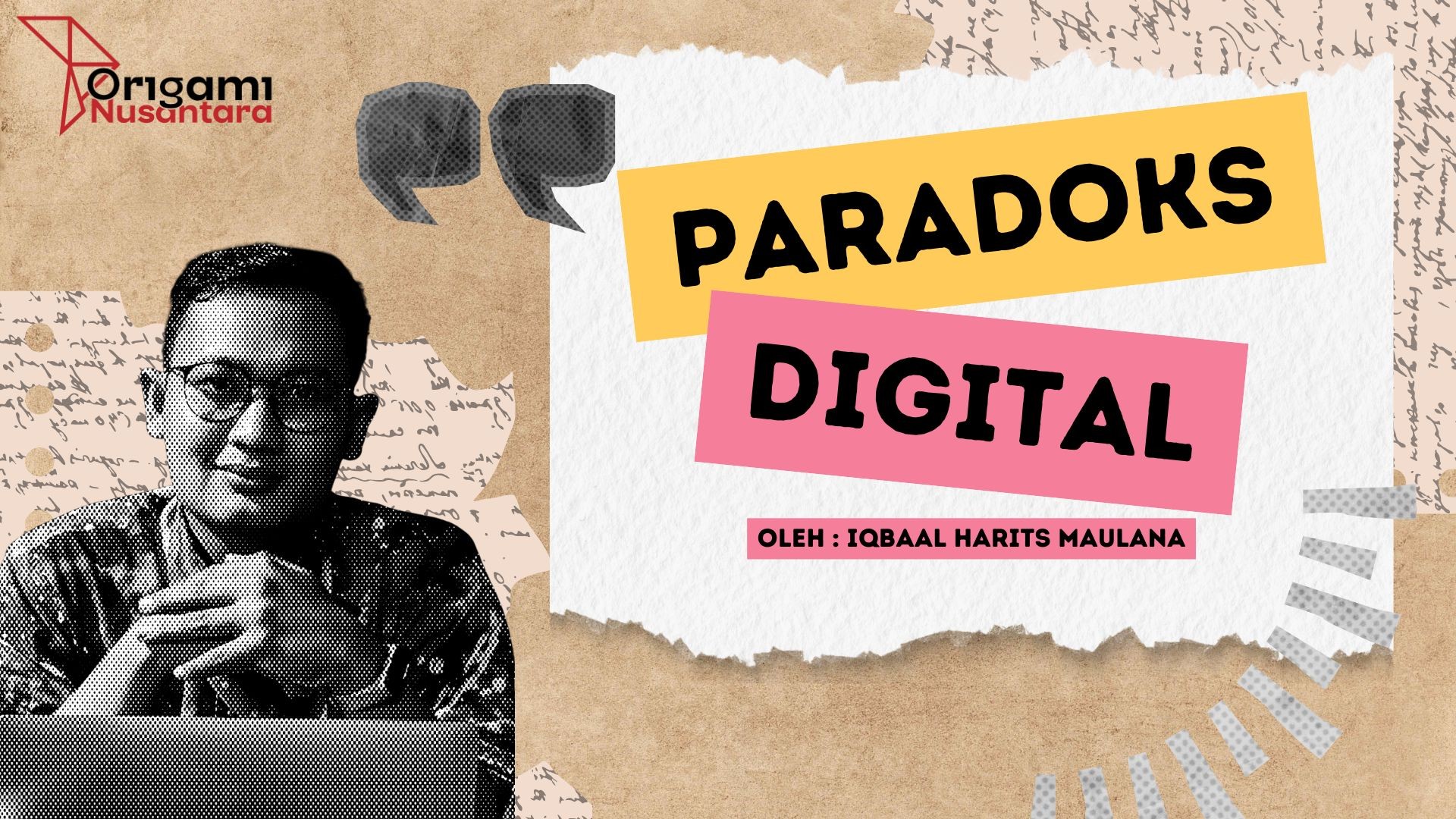
Keterangan Gambar : Paradoks Digital diruang Demokrasi
Ada sebuah peristiwa yang mungkin sepintas terdengar mustahil. Nepal, sebuah negara kecil di Himalaya yang selama ini lebih sering dikaitkan dengan puncak Everest daripada dengan teknologi digital, tiba-tiba mengguncang dunia. Setelah gelombang protes besar, generasi muda di sana menggunakan platform Discord aplikasi yang lazim dipakai untuk bermain gim atau bercakap santai untuk melakukan polling pemilihan perdana menteri sementara. Hasil polling itu kemudian mengantarkan Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, menjadi pemimpin interim yang sah.
Apakah ini sah menurut konstitusi? Apakah ini bisa disebut demokrasi digital yang utuh? Pertanyaan-pertanyaan itu memang masih menunggu jawaban. Namun, satu hal pasti: peristiwa tersebut adalah tanda zaman. Bahwa digitalisasi bukan lagi sesuatu yang bisa dianggap sebagai tren belaka. Ia adalah keniscayaan. Ia merasuk ke dalam seluruh lini kehidupan, bahkan ke ruang-ruang paling sakral yang sebelumnya tak tersentuh.
Baca Lainnya :
Kita bisa saja masih meragukan keabsahan pemilu lewat Discord, tetapi kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa teknologi telah memainkan peran luar biasa. Hal yang dulu dianggap sebelah mata sekadar aplikasi obrolan digital ternyata bisa membuka jalan bagi lahirnya kepemimpinan baru di sebuah negara. Itulah wajah nyata dari disrupsi digital.
Fenomena di Nepal seharusnya menjadi cermin bagi kita di Indonesia. Kita hidup di era ketika digitalisasi tidak lagi sebatas pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Lembaga-lembaga yang menutup mata, menolak beradaptasi, atau merasa nyaman dengan cara-cara lama, lambat laun akan semakin tertinggal. Dunia bergerak cepat, dan mereka yang enggan bergerak akan ditinggalkan.
Namun, digitalisasi bukan tanpa sisi gelap. Di Indonesia, kita menyaksikan bagaimana media sosial menjadi arena pertempuran wacana yang begitu dahsyat. Gelombang protes pada 25–31 Agustus 2025 yang melanda berbagai kota diyakini sebagian pihak tidak lepas dari peran algoritma media sosial. Informasi baik yang benar maupun menyesatkan menyebar dengan kecepatan kilat. Provokasi diproduksi dan diperbanyak, lalu menjalar ke ruang-ruang publik. Dalam hitungan jam, situasi sosial bisa memanas, dan ribuan orang bisa turun ke jalan.
Inilah paradoks digitalisasi. Di satu sisi, ia membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, memungkinkan suara rakyat terhimpun dengan cepat, dan memberi peluang demokrasi berjalan lebih dinamis. Di sisi lain, ia juga menghadirkan kerentanan yang nyata: disinformasi, polarisasi, bahkan potensi instabilitas politik.
Lalu, apakah jawabannya adalah menolak digitalisasi? Tentu tidak. Justru jawaban terbaik adalah mengelolanya. Kita harus membangun kesadaran bahwa digitalisasi adalah arus deras yang tidak bisa dibendung, tetapi bisa diarahkan. Negara harus hadir dengan regulasi yang cerdas dan adaptif. Lembaga demokrasi harus belajar memanfaatkan teknologi bukan hanya sebagai instrumen komunikasi, tetapi juga sebagai alat transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat sipil pun harus diperlengkapi dengan literasi digital yang memadai, agar tidak mudah menjadi korban manipulasi algoritma atau terpancing oleh provokasi murahan.
Kisah Nepal menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi wadah lahirnya perubahan. Sementara pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa teknologi juga bisa menjadi alat untuk memperuncing konflik sosial. Dua sisi koin yang sama, dua wajah dari satu keniscayaan.
Maka, tantangan kita bukan lagi soal menerima atau menolak digitalisasi, melainkan bagaimana menata dan mengelolanya. Jika dikelola dengan bijak, digitalisasi bisa memperkuat demokrasi, mempercepat pembangunan, dan memperluas partisipasi rakyat. Tetapi jika dibiarkan tanpa arah, ia bisa menimbulkan kekacauan yang tak kalah besar.
Peristiwa di Nepal adalah alarm bagi kita semua. Dunia sedang berubah. Cara kita berpolitik, berdemokrasi, bahkan memilih pemimpin pun sedang berubah. Tidak ada institusi yang kebal terhadap digitalisasi. Menutup mata hanya berarti semakin jauh tertinggal.
Indonesia, dengan jumlah penduduk muda yang besar dan penetrasi internet yang luas, memiliki peluang sekaligus risiko yang sama besarnya. Pilihan ada di tangan kita, apakah kita akan menjadi penonton yang gagap menghadapi arus digitalisasi, ataukah kita siap menjadi pemain utama yang bijak mengelola perubahan?
Karena pada akhirnya, digitalisasi bukan sekadar alat. Ia adalah keniscayaan yang sedang menulis ulang sejarah manusia.

.png)

.jpg)
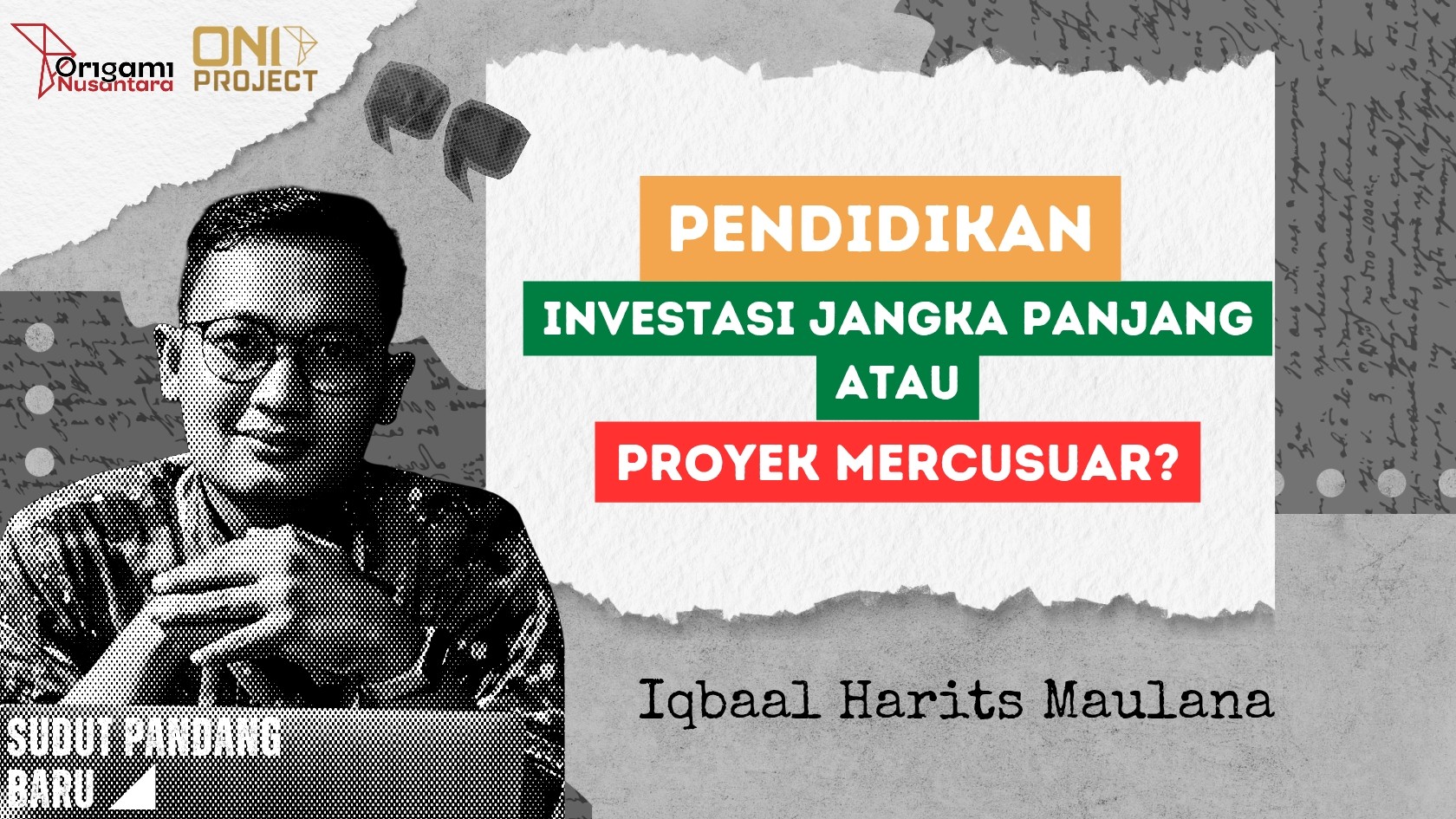
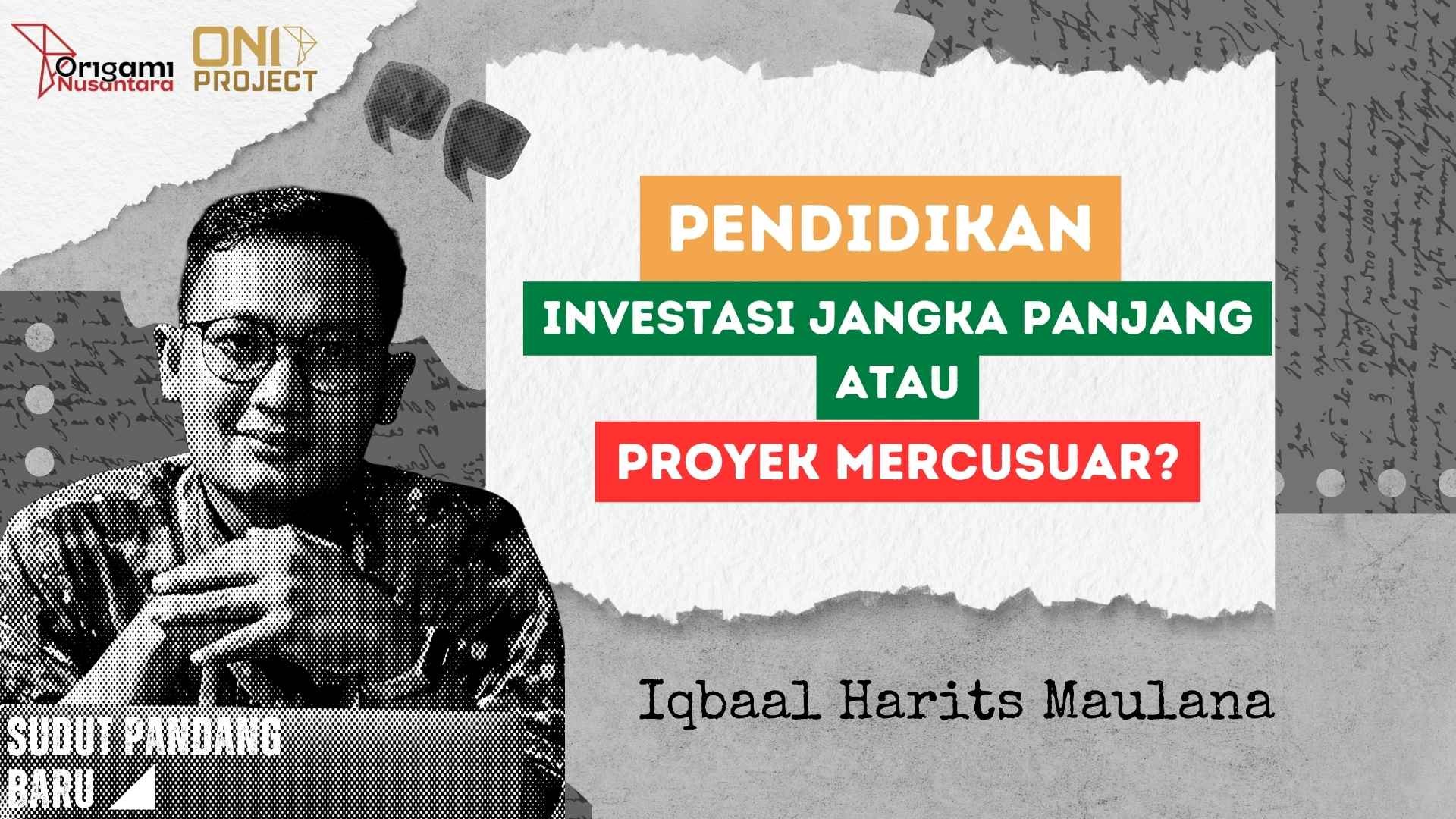
.jpg)
.jpg)
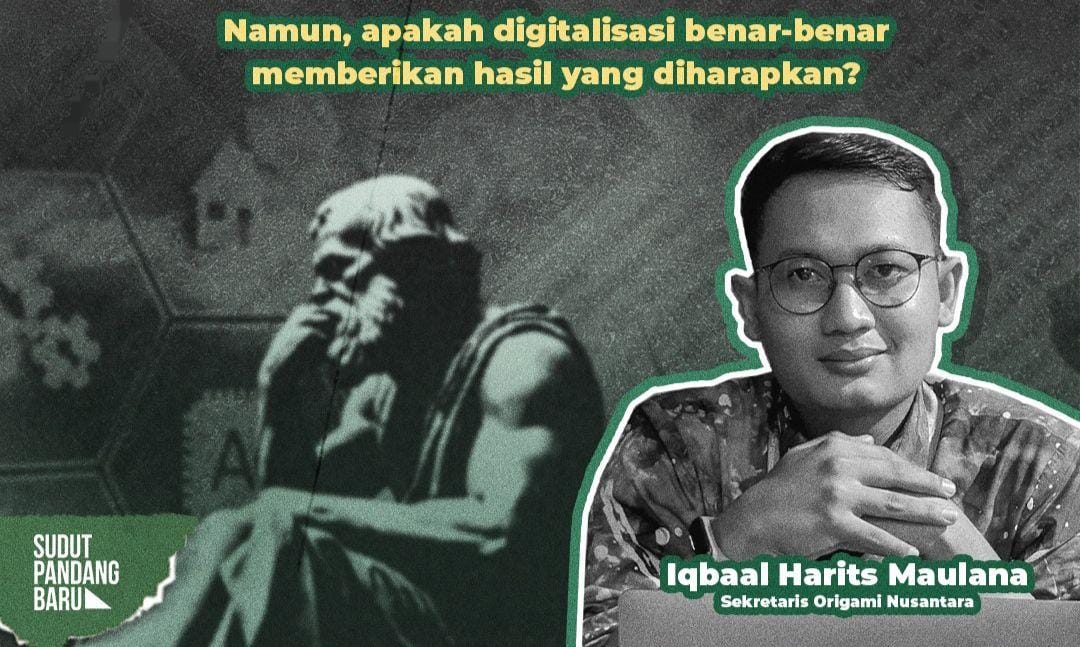
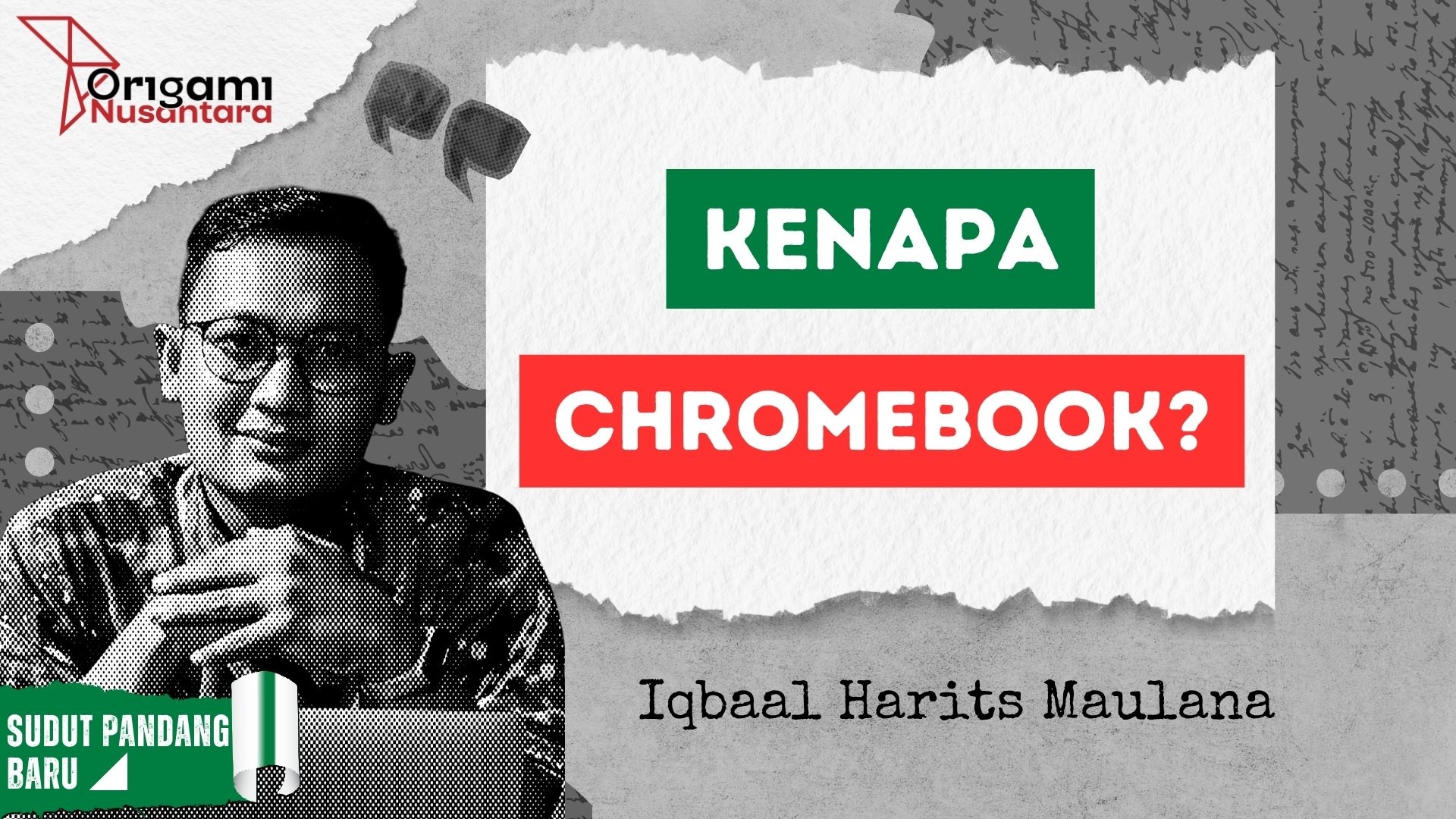
.jpg)
.jpg)